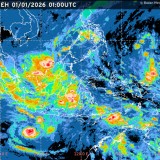TIMES TANGSEL, JAKARTA – Indonesia sepanjang tahun 2025 mencatat kemajuan pesat di bidang teknologi digital. Tingkat penetrasi internet nasional menembus 80,66% populasi (sekitar 229 juta penduduk terkoneksi internet dari total 284 juta), meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Adopsi teknologi 5G dan kecerdasan buatan (AI) mulai meluas di berbagai sektor, memperkuat transformasi digital ekonomi. Ironisnya, di tengah majunya infrastruktur digital dan ramainya inovasi teknologi, muncul bayang-bayang ancaman baru: algoritma di platform digital dimanfaatkan sebagai senjata dalam “perang” era baru untuk memecah belah dari dalam negeri.
 Peta transformasi digital Indonesia 2025 menunjukkan penetrasi internet yang tinggi, adopsi AI dan 5G yang meluas, sekaligus meningkatnya kerentanan baru di ruang siber.
Peta transformasi digital Indonesia 2025 menunjukkan penetrasi internet yang tinggi, adopsi AI dan 5G yang meluas, sekaligus meningkatnya kerentanan baru di ruang siber.
Fenomena proxy war berbasis algoritma ini menandai babak baru hubungan antara teknologi dan stabilitas sosial-politik Indonesia tahun 2025.
Apa dan bagaimana perkembangan teknologi 2025, bagaimana pula di 2026? Berikut news analysis dan ulasan M. Theofany Aulia, mahasiswa Magister Teknologi AI, UGM.
*
Perkembangan pesat teknologi di Indonesia pada 2025 memberikan landasan bagi konektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan lebih dari 80% penduduk terkoneksi internet, masyarakat Indonesia semakin aktif di ruang digital untuk berkomunikasi, berbelanja, hingga berpolitik.
Generasi muda (Gen Z dan milenial) mendominasi pengguna internet, memanfaatkan media sosial dan e-commerce secara masif. Di sisi lain, kemajuan ini juga didorong oleh pengembangan jaringan 5G di kota-kota besar serta maraknya inovasi AI generatif dalam layanan publik dan bisnis.
Pemerintah pun mulai menyusun regulasi khusus AI agar teknologi cerdas dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Semua capaian ini menegaskan bahwa teknologi digital kian menjadi tulang punggung kehidupan nasional.
Namun, kemajuan tersebut datang bersama tantangan internal. Supremasi algoritma di platform digital perlahan “mendikte” arus informasi publik. Media sosial dapat menyebarkan kabar dalam sekejap, bahkan mengungguli kecepatan media arus utama. Akibatnya, media tradisional menghadapi tekanan berat untuk tetap relevan di era algoritma yang mengutamakan clickbait dan sensasi.
Dewan Pers tahun 2025 pun menyoroti dominasi algoritma sebagai ancaman baru bagi ekosistem pers. Bukan lagi semata tekanan politik, tetapi jebakan algoritmis yang menentukan apa yang dilihat publik.
Dengan konteks itulah, tantangan utama bukan pada kurangnya teknologi, melainkan bagaimana teknologi yang maju justru bisa “menyerang” dari dalam melalui mekanisme algoritma.
Algoritma Adu Domba: Proxy War di Era Digital
 Ilustrasi algoritma media sosial sebagai “pedang bermata dua” dalam perang hibrida modern: mempercepat arus informasi sekaligus memicu konflik sosial dan polarisasi di dalam negeri.
Ilustrasi algoritma media sosial sebagai “pedang bermata dua” dalam perang hibrida modern: mempercepat arus informasi sekaligus memicu konflik sosial dan polarisasi di dalam negeri.
Kemajuan teknologi digital bak pedang bermata dua. Sepanjang 2025, marak beredar konten provokatif bernuansa adu domba di media sosial, yang bahkan sempat masuk jajaran tren teratas di linimasa.
Unggahan-unggahan bernarasi SARA, seperti provokasi Aceh merdeka, hasutan pertentangan antara suku (misalnya Sunda vs Jawa, Madura vs Jawa), isu penduduk asli vs pendatang (contoh di Bali), hingga upaya mengadu domba tokoh agama (kyai vs habaib), bermunculan dan berpotensi mengganggu persatuan nasional.
Pattern pola sebaran konten semacam ini tidak dianggap sebagai dinamika warganet biasa, melainkan bagian dari skenario perang hibrida modern yang memanfaatkan algoritma platform digital untuk melemahkan bangsa dari dalam.
Para pengamat keamanan siber menilai bahwa pola proxy war digital ini bekerja dengan cara memicu gesekan sosial melalui disinformasi dan ujaran kebencian yang sengaja ditebar. Tujuan akhirnya jelas berbahaya: menciptakan kekacauan, konflik horizontal berkepanjangan, dan bahkan delegitimasi pemerintahan yang sah.
Metode seperti ini bukan isapan jempol belaka. Rekam jejaknya pernah terlihat di sejumlah negara Timur Tengah, di mana propaganda digital yang mengadu kelompok masyarakat berujung perang saudara dan membuka jalan intervensi asing. Dengan kata lain, algoritma media sosial telah menjadi senjata baru untuk melumpuhkan suatu negara dari dalam tanpa perlu invasi militer terbuka.
Bagaimana algoritma berperan? Di ranah digital, algoritma platform seperti Facebook, YouTube, TikTok, hingga Twitter dirancang untuk memaksimalkan atensi pengguna, seringkali dengan memprioritaskan konten bermuatan emosional. Akibatnya, posting bernada ekstrem, provokatif, atau penuh amarah justru mendapat jangkauan lebih luas dibanding informasi akurat yang netral.
 Skema kerja algoritma platform digital yang memprioritaskan konten emosional, membentuk filter bubble dan echo chamber, hingga memperdalam polarisasi publik.
Skema kerja algoritma platform digital yang memprioritaskan konten emosional, membentuk filter bubble dan echo chamber, hingga memperdalam polarisasi publik.
Gesekan kecil yang dibiarkan dapat membesar menjadi konflik terbuka. Di ruang digital, algoritma memperkuat konten ekstrem karena memicu emosi, sehingga persebarannya semakin cepat.
Kasus nyata terlihat saat beredar luas video pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan aparat di akhir Agustus. Video unggahan warga tersebut viral seketika, memicu gelombang simpati bercampur amarah yang menyulut eskalasi demonstrasi di lapangan.
Algoritma menyaring informasi berdasarkan engagement (interaksi); akibatnya konten tragis nan emosional itu diutamakan, mengalahkan klarifikasi resmi yang mungkin lebih akurat.
Fenomena ini bak dua sisi mata uang. Positifnya, solidaritas publik bisa terbentuk cepat, suara warga kecil mendadak terdengar luas. Namun di sisi lain, arus informasi yang dikendalikan algoritma membuka celah disinformasi: hoaks, rekayasa foto/video, dan konten manipulatif mudah terselip, memperkeruh keadaan.
Ketika literasi digital masyarakat masih lemah, publik mudah terjebak narasi yang belum tentu benar. Inilah ladang subur bagi “algoritma adu domba” bekerja: memperkuat bias kelompok (melalui filter bubble dan echo chamber), sehingga orang hanya terpapar sudut pandang yang mengipasi kemarahan kelompoknya sendiri. Ujungnya, empati antar-kelompok menipis dan polarisasi kian tajam.
Demo Agustus 2025: Bukti Nyata Guncangan Algoritma
 Infografik demonstrasi nasional 25–30 Agustus 2025 yang menunjukkan bagaimana isu viral, algoritma media sosial, dan AI membentuk mobilisasi massa tanpa komando sentral, namun bergerak terkoordinasi mengikuti linimasa digital.
Infografik demonstrasi nasional 25–30 Agustus 2025 yang menunjukkan bagaimana isu viral, algoritma media sosial, dan AI membentuk mobilisasi massa tanpa komando sentral, namun bergerak terkoordinasi mengikuti linimasa digital.
Gelombang unjuk rasa nasional akhir Agustus 2025 menjadi contoh paling mencolok bagaimana algoritma digital mengubah dinamika gerakan sosial. Demonstrasi besar-besaran 25–30 Agustus 2025 awalnya dipicu isu kebijakan tunjangan DPR dan pajak yang mencekik, tetapi meluas menjadi letupan kemarahan rakyat terhadap ketimpangan, kekerasan aparat, hingga krisis kepercayaan pada pemerintah.
Jika di era Reformasi 1998 aksi turun ke jalan dipandu tokoh jelas dengan manifesto terstruktur, aksi 2025 ini justru bergerak nyaris tanpa “komando” sentral. Mantan aktivis 98 Budiman Sudjatmiko bahkan menyebut kerusuhan demo 28–30 Agustus 2025 sebagai peristiwa unik pertama di sejarah Indonesia modern yang “dikendalikan oleh algoritma dan AI”.
“Sekarang ini mungkin demonstrasi pertama di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma,” tegas Budiman menggambarkan berubahnya pola pergerakan massa.
Pernyataan Budiman bukan tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa teknologi media sosial mampu menggerakkan massa, bahkan memungkinkan aktor di luar negeri turut mengatur jalannya aksi dengan memanfaatkan algoritma sentimen sosial.
“Saya mungkin ada di Manila, saya bisa memerintahkan lewat YouTube, TikTok, Instagram, atau kanal lain untuk menyusun tuntutan yang bisa berubah tiap hari. Semua itu disebar dengan cepat sesuai algoritma sentimen pagi itu,” ujar Budiman memberi ilustrasi.
Dalam skenario seperti ini, media sosial bukan sekadar medium komunikasi, melainkan “ruang komando” virtual yang terdesentralisasi. Tuntutan aksi bisa berganti setiap hari mengikuti isu terpanas di linimasa, seolah agenda demo ditentukan oleh trending topic harian.
Bahkan, Budiman menambahkan, kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT kini mampu membantu merumuskan slogan dan tuntutan aksi yang selaras dengan psikologi massa di berbagai kota secara instan. Hal ini membuat orkestrasi gerakan massa secara real-time menjadi mungkin. Sesuatu yang nyaris mustahil di era sebelum platform digital sedemikian berpengaruh.
Dampak “dikendalikan algoritma” ini terlihat jelas di lapangan. Di Jakarta dan puluhan kota lain, demonstrasi bergerak serentak tanpa koordinasi formal, dipicu isu viral yang menyebar online dalam hitungan jam.
Pasca tewasnya pengemudi ojek online yang viral tadi, amarah massa memuncak spontan. Kericuhan menjalar ke mana-mana bagai api tersulut bensin digital. Kelompok misterius tak dikenal muncul memprovokasi bentrokan di beberapa daerah, memanfaatkan situasi chaos.
Ini mengindikasikan pola “controlled chaos”, di mana kekacauan sengaja dipicu lalu “digiring” untuk membentuk persepsi publik tertentu. Terbukti, pasca demo mereda, muncul dua narasi berseberangan di ruang publik: versi aparat yang menyalahkan provokator eksternal vs versi aktivis/sipil yang menyalahkan aparat sebagai biang kekerasan.
Polarisasi opini pasca demo ini diperkuat oleh algoritma echo chamber di media sosial, yang “mengurung” pengguna dalam lingkaran narasi searah. Akibatnya, alih-alih dialog, yang terjadi adalah perang persepsi – masing-masing kelompok bersikukuh pada versinya dan saling delegitimasi.
Kasus demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan bahwa teknologi dan algoritma kini menjadi faktor penggerak utama dalam dinamika politik jalanan. Gerakan massa di era digital dapat tumbuh laksana gelombang tsunami: bermula dari pusaran kecil di media sosial, kemudian meluas cepat melampaui kendali struktur tradisional.
Mobilisasi fisik di jalan raya kerap kali bermula dari momentum di dunia maya, dan sebaliknya, apa yang terjadi di jalanan langsung kembali menggemakan percakapan di internet, menciptakan lingkaran umpan balik yang saling menguatkan.
Inilah realitas baru hubungan teknologi dan demokrasi Indonesia: media sosial menjadi arena protes yang sama pentingnya dengan jalanan. Tantangannya, tanpa mitigasi, “bara digital” ini bisa terus menyulut perpecahan jika dibiarkan.
Algoritma untuk Delegitimasi Pemerintah
 Ilustrasi pergeseran solidaritas publik menjadi polarisasi politik di ruang digital, ketika simbol perlawanan viral diproduksi ulang algoritma hingga berpotensi mendelegitimasi kepercayaan terhadap institusi negara.
Ilustrasi pergeseran solidaritas publik menjadi polarisasi politik di ruang digital, ketika simbol perlawanan viral diproduksi ulang algoritma hingga berpotensi mendelegitimasi kepercayaan terhadap institusi negara.
Selain mengadu domba antarkelompok masyarakat, senjata algoritma digital juga diarahkan untuk menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tahun 2025, kita melihat fenomena bagaimana narasi di media sosial dapat mengubah persepsi rakyat terhadap negara secara drastis. Misalnya, dari rangkaian demo Agustus tadi, lahir sebuah simbol gerakan bernama “Brave Pink” – diambil dari ikon viral seorang ibu berjilbab pink yang berani menghadang aparat.
Brave Pink awalnya simbol solidaritas warga, bersanding dengan “Hero Green” (ikon pengemudi ojek online korban tewas) dan “Resistance Blue”. Ribuan netizen mengganti foto profil dengan ikon-ikon warna itu sebagai bentuk dukungan. Fenomena ini menyatukan keresahan rakyat menjadi narasi bersama di dunia maya.
Namun, simbol perlawanan tersebut juga dihadapkan pada risiko politisasi oleh algoritma. Polarisasi digital yang terus diperkuat algoritma media sosial dapat mempercepat fragmentasi politik di masyarakat. Jika simbol-simbol seperti Brave Pink ditafsirkan secara biner – pro-rakyat vs pro-negara – dan narasi “rakyat melawan negara” makin menguat di linimasa, maka lambat laun Brave Pink bisa bergeser makna: dari sekadar simbol solidaritas menjadi simbol delegitimasi pemerintah.
Artinya, gerakan sosial yang sebenarnya berangkat dari kritik konstruktif, oleh algoritma dapat dibelokkan menjadi seolah-olah ancaman terhadap keabsahan negara. Narasi bahwa “rezim zalim melawan rakyatnya sendiri” misalnya, jika terus digaungkan tanpa kontrol, akan mengikis legitimasi institusi pemerintah di mata publik.
Perlu digarisbawahi, tidak semua kritik atau gerakan protes otomatis mengancam keamanan nasional. Justru, demokrasi yang sehat membutuhkan kritik untuk menjaga negara tetap di jalur benar. Namun, ancaman muncul ketika pemerintah keliru menanggapi – misal dengan tindakan represif yang berlebihan.
Tanggapan keras justru memperkuat narasi perlawanan tadi dan memberi pembenaran pada opini bahwa pemerintah anti-rakyat. Di sinilah algoritma “adu domba nasional” berperan mengipasi api: setiap tindakan aparat yang keras akan diviralkan dengan framing negatif, sementara prestasi atau klarifikasi positif tenggelam dalam keributan.
Krisis kepercayaan pun bisa memburuk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengingatkan bahwa fitnah, hoaks, dan adu domba yang marak di dunia digital belakangan ini menjadi perhatian serius, karena “narasi ‘rakyat vs negara’ kalau dibiarkan akan menjelma ancaman nyata bagi persatuan”.
Pemerintah pun akhirnya dituntut lebih bijak: membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi, daripada reaksi berlebihan yang justru kontraproduktif.
Kasus Brave Pink dan demo 2025 memberi pelajaran berharga. Keamanan nasional di era digital tidak lagi semata soal ancaman militer, tapi juga soal terjaganya kepercayaan rakyat. Algoritma media sosial telah menjadi arena pertempuran baru bagi opini publik.
Jika dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab, algoritma bisa menjadi alat subversi yang halus tapi menghujam: merusak wibawa pemerintah, memecah belah masyarakat, melumpuhkan dari dalam. Oleh karena itu, delegitimasi pemerintah melalui algoritma harus diwaspadai sebagai ancaman “perang hibrida” gaya baru di Indonesia.
Menangkal "Perang" Algoritma: Literasi dan Kebijakan

Menghadapi bayang-bayang perang algoritma adu domba ini, berbagai upaya mitigasi mulai digencarkan sepanjang 2025. Pemerintah, lembaga, hingga komunitas sipil menyadari perlunya strategi defensif dan kuratif. alApa saja?
Pertama, literasi digital massal. Edukasi publik agar lebih cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan membagikan unggahan bernarasi negatif yang berpotensi memecah belah, serta selalu cek fakta sebelum bereaksi.
Upaya kolaboratif oleh pemerintah, kampus, dan pegiat IT dilakukan untuk sosialisasi digital literacy sampai ke daerah.
Kedua, kontrol konten provokatif. Aparat dan platform media sosial meningkatkan patroli siber terhadap akun-akun anonim penyebar hasutan. Langkah tegas termasuk pelaporan dan penindakan hukum bagi penyebar ujaran kebencian dan disinformasi diterapkan.
Tahun 2025, beberapa kali Kepolisian mengumumkan penangkapan admin grup Facebook/WhatsApp yang memicu isu SARA, menunjukkan sinyal penegakan hukum di ranah ini.
Ketiga, transparansi algoritma. Dorongan agar raksasa platform digital lebih transparan dan bertanggung jawab atas algoritma rekomendasi mereka semakin kuat. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo berdialog dengan perusahaan medsos untuk memastikan algoritma tidak sengaja “mengkompori” konten berbahaya demi engagement. Wacana regulasi untuk mengawasi algorithms fairness juga muncul, sejalan dengan tren global mengendalikan dampak negatif Big Tech.
Keempat, penguatan jurnalisme dan counter-narrative. Insan pers ditantang untuk lebih proaktif meluruskan hoaks dan menyajikan liputan bernutrisi yang menjembatani perbedaan.
Dewan Pers mengingatkan media agar jangan terjebak euforia kedekatan dengan penguasa atau klik semata, melainkan tetap mengedepankan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Narasi-narasi positif tentang toleransi, persatuan, dan keberagaman bangsa diperbanyak sebagai penyeimbang derasnya arus ujaran kebencian.
Misalnya, muncul kampanye damai lintas agama di media sosial yang sengaja di-boost oleh komunitas influencer untuk meredam sentimen SARA.
Upaya-upaya di atas tentunya membutuhkan partisipasi semua pihak. Persatuan dan kewaspadaan publik adalah kunci menghadapi tantangan algoritma adu domba ini. Seperti pepatah, “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Masyarakat perlu menyadari bahwa kerap kali lawan terbesar datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri – dari bagaimana kita bereaksi terhadap provokasi digital.
Teknologi hanyalah alat, apakah ia akan menjadi jembatan menuju demokrasi lebih inklusif, atau justru bara yang menyulut perpecahan, sepenuhnya ditentukan oleh kebijaksanaan penggunanya
Sepanjang 2025 ini, Indonesia belajar bahwa kemajuan teknologi digital harus diiringi dengan kematangan literasi. Di bawah bayang-bayang ancaman “perang algoritma”, bangsa ini terpanggil untuk makin cerdas dan bersatu.
Tahun 2025 tutup dengan harapan: di masa depan, algoritma dan AI yang ada bukan lagi menjadi alat adu domba, melainkan dipakai untuk mempererat persatuan dan memperkokoh demokrasi. (*)
Sumber literasi:
1). Abu Sofian. “Peran Algoritma Media Sosial dalam Dinamika Unjuk Rasa Indonesia.” Indonesiana – Tempo, 31 Agustus 2025.
2). Budiman Sudjatmiko. Pernyataan di tvOne News, 3 September 2025.
3). Fakta Kini. “Algoritma Adu Domba Nasional: Ancaman Perang Hibrida di Ruang Digital.” 30 Desember 2025.
4). Nazwa N. Zahra. “Apakah Brave Pink Mengancam Keamanan Nasional Indonesia?” FISIP UIN Jakarta, 10 Oktober 2025.
5). Josua. “APJII 2025: Penetrasi Internet Indonesia 80,66%.” DASWATI Lampung, 14 November 2025.
6). Ruben C. Siagian. “Gerakan Rakyat atau Rekayasa Kekuasaan? (Demonstrasi Agustus 2025).” Birokrat Menulis, 17 Oktober 2025.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Menutup 2025, Menatap 2026: Teknologi Maju dan Algoritma Adu Domba
| Pewarta | : Theofany Aulia (DJ-999) |
| Editor | : Deasy Mayasari |